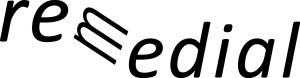Imaji orang-orang kampung mengenai imlek adalah Tepekong. Arak-arakan ini selalu ditunggu dan menjadi nostalgia imaji pikiran bocah SD saya. Di hari itu orang-orang di kampung saya akan menonton semarak arak-arakan itu. Saya yang masih bocah saat itu menonton Tepekong adalah imaji terbaik, saat berdesak-desakan menonton arak-arakan dengan warna merah itu.
“Itu semua akibat Gus Dur,” celoteh orang dari kejauhan.
Saya belum mengerti mengapa Gusdur dikaitkan dengan arak-arakan itu. Orang-orang di kampung mungkin mengenal televisi dan melihat sepak terjang Gusdur bagi orang-orang Tionghoa di Indonesia. Bagi saya televisi adalah dunia baru saya diperkenalkan dengan budaya-budaya Tionghoa lewat layar kaca. Arak-arakan Tepekong yang saya lihat menambah imaji saya tentang budaya Tionghoa yang ada di Televisi semisal perkenalan dengan film “Once Upon A Time” yang sering tampil di Televisi. Sampai suatu ketika sayamengerti saat menginjakan kaki ke Mojokerto bertemu dengan patung Gusdur yang sedang tidur seperti Budha. Atau ketika bertemu dengan buku Lan Fang Imlek Tanpa Gusdur (2012) .

Imlek juga adalah perjumpaan saya dengan makanan-makanan khas Tionghoa. Makanan itu hadir dibawa ibu saya dari pemilik toko kelontong langganannya. Di hari itu ibu saya yang sudah 10 tahun menjadi pelanggan toko kelontong sering mendapatkan makanan semisal dodol cina atau kue keranjang. Saya yang saat itu sesekali diajak ke toko kelontong tersebut melihat bagaimana ibu saya dapat tertawa dengan pemilik toko saat ngobrol sembari menyebutkan barang-barang yang akan dibelinya. Itu pula yang menurut saya pengalaman-pengalaman itu membentuk imaji bocah saya untuk tak mendeskritkan orang-orang Tionghoa yang seakan-akan dibilang pelit dan sebagainya.
Perjumpaan biografis saya dengan orang-orang keturunan Tionghoa berlanjut pada referensi buku-buku mengenai ornag-orang keturuanan Tionghoa barangkali saat membeli beberapa buku kecil cerita silat Ko Ping Ho saat kuliah. Yang paling mengesankan adalah kita saya berjumpa dengan buku “Sastera Indonesia Tionghoa” (1957) karya Ni Jo Lan. Buku itu saya dapatkan saat bertandang ke Solo. Dan saat Imlek tahun 2015 buku itu menjadi bahan diskusi. Karena saat imlek tiba perbincangan mengenai imlek tak sekadar hanya bakmi, dodol cina tapi juga ingatan-ingatan mengenai pustaka penulis peranakan Tionghoa yang mengadar di Indonesia. Ni Jo Lan dalam kata pengantarnya mengatakan,“hasil sastera itu merupakan tipifikasi suatu zaman jang sudah silam, sedjarah kemasjarakatan suatu golongan bangsa di Indonesia kita pada masa itu, dan alat penundjuk angan-angan jang hidup dalam golongan itu”.
Leo Suryadinata mengatakan Ni Jo Lan merupakan tokoh penting yang menulis tentang sejarah sastra tionghoa peranakan. Tahun demi tahun, Ni Jo Lan pun senyap karena jarang didiskusikan buku-bukunya. Pramoedya Ananta Toer-lah sastrawan Indonesia yang memulai memasukan karya-karya sastra peranakan Tionghoa ini. Pram mengamini apa yang dikhawatirkan oleh Ni Jo Lan bahwa jika tidak ada penelitian lebih lanjut sastra tionghoa peranakan akan hilang begitu saja. Ni Jo Lan (1957) gelisah dengan menulis,“sastera ini akan lenjap terseret arus sang Kala”. Ni Jo Lan banyak mengajukan penulis-penulis Tionghoa peranakan yang banyak menerbitkan karyanya sebagai pemuas dahaga akan bacaaan sastra Tionghoa.
Djames Danandjaya pernah menulis tentang Folklor Tionghoa (2007). Djames Danandjaya menulis buku itu sebagai upaya mengobati amnesia sejarah. Menurut Djames Danandjaya suku bangsa mayoritas Indonesia mengalami hypnoticamnesia sedangkan suku bangsa Tionghoa adalah autohypnotic amnesia. Patut menjadi catatan adalah mengenai autohpynotic amnesia ini. Djames Danandjaya mengatakan autohypnotic amnesia disebabkan oleh penguasa. Indoktrinasi yang dilakukan oleh penguasa Orba berupa pelarangan sekolah dan penerbitan berbahasa Cina, penggantian nama, pelarangan upacara di depan umum menyebabkan suku bangsa Tionghoa melupakan jati dirinya. Dalam kata pengantar Djames Danandjaya menulis, “Akibat indoktrinisasi yang dilakukan secara sitematik itu, kebanyakan orang tionghoa karena patuh pada politik pemerintah Orba dengan sadar atau tidak sadar telah melupakan jati dirinya”. Dan ini tak hanya terjadi di etnik Tionghoa saja.

Di era reformasi Gusdur membawa angin segar bagi perkembangan sastra yinhua ini. Agus Setiadi (2010) dalam esainya “Geliat Sang Naga Dalam Pustaka” mencatat beberapa buku yang hadir menghias di toko buku setelah reformasi. Kita pun dapat mencatat novel-novel yang hadir menjadi referensi membaca sang naga dalam pustaka. Remy Sylado salah satu sastrawan yang rajin menulis novel bernuansa Tionghoa. Kita bisa mengingat karya-karya Remy seperti Siau LingCau Bau Kan, Sam Po Kong Perjalanan Pertama. Ataupun karya terjemahan Pramoedya Annata Toer berupa Dewi Uban dan Opera Lima Babak. Ingatan-ingatan mengenai buku itu barangkali mengingatkan saya juga padasebuah toko buku bekas di daerah Grogol, saya sering berjumpa dengan pemilik toko buku yang sering saya panggil “Akoh”. Dari ia pula perjumpaan saya dengan buku-buku sekaligus perjumpaan yang pada akhirnya menghadirkan tawa saat penawaran harga. Maupun saat ia tak segan-segan menjual beberapa majalah Tempo dengan murahnya kepada saya.
Melawan Sekat Itu
Di tengah sekat-sekat pribumi dan non pribumi yang kembali menjadi wajah bopeng dibutuhkan karya sastra maupun karya seni rupa sebagai pembacaan kembali mengenai takhyaul rasial pribumi dan non pribumi. Ariel Heryanto mengatakan kepribumian mirip dinosaurus yang dihidupkan kembali di pabrik takhayul bernama Hollywood. Seperti industri takhayul rasial pribumi dan non pribumi akan dibuat karena ada politik kepentingan kekuasaan. Sebab itu ia tidak sepele. Gempuran rasial ini terus diproduksi di media sosial dan juga ruang-ruang produksi kultur seperti sekolah, rumah, maupun ruang-ruang negara. Kita sering saling serang : lewat wacana ketakutan akan orang lain. Di mana ketakutan itu muncul ketika berkaitan dengan agama, ekonomi, kultur, dan nasionalisme semu.

Kehadiran Jessica dan Andrea selama proses residensi di Gudang Sarinah Ekosistem (GSE) bersama Serrum sampai pameran merupakan jawaban menawarkan gagasan dari pengalaman perlawanan politik rasial melalui karya seni rupa.Inside/Outside adalah gagasan tema maupun konsep visualisasi mereka barangkali membuka wajah bopeng kita yang sering diserang politik rasial ini. Keduanya menawarkan gagasan yang tak sepele. Pengalaman yang tumbuh akibat produksi kultur di sekolah, keluarga, maupun ruang-ruang privat dan publik lainnya menjadi cermin wajah kita hari ini. Keduanya mengajak kita keluar dari takhayul rasial.
Rianto
Serrum dan Tim Remedial